Msuknya agama Islam dan perkembangan komunitas Muslim di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa sesungguhnya sudah berlangsung lama, sejak Kerajaan Majapahit masih sangat berkuasa. Namun seiring misi perdagangan yang menyertai kehadiran dan keberadaannya, aktifitas komunitas ini masih sangat berjarak dengan dinamika politik di tanah Jawa masa itu, kecuali sebatas aktifitas ekonomi, sosial dan budaya.
Peta ini segera berubah ketika kekuasaan Majapahit mulai surut dan disusul dengan munculnya pusat-pusat kekuasaan Islam, khususnya di Demak, Banten dan Cirebon. Pada saat yang sama, persaingan dakwah dan perniagaan di kawasan Asia Tenggara meningkat pesat, terlebih dengan jatuhnya Malaka (1511) dan Samudera pasai (1512) ke tangan Portugis. Demak, Banten dan Cirebon pun sempat beraliansi merapatkan barisan untuk mencegah pengaruh dominasi Portugis di tanah Jawa.
Bermula dari sebuah kadipaten di wilayah pesisir, Demak muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi kebesaran Majapahit yang semakin surut. Kota pelabuhan ini dibangun pada tahun 1475 oleh Raden Patah yang kemudian bertahta sebagai Sultan Demak I dengan gelar Alam Akbar al Fattah (1500-1518).
Raden Patah dikenal sebagai pemimpin yang sangat toleran. Kuil Sam Po Kong di Semarang yang dibangun oleh Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam, tidak dipaksa untuk mengembalikan fungsinya sebagai masjid. Atas wasiat Sunan Ampel, Raden Patah juga tidak mau memerangi umat Hindu dan Buddha. Meski sempat melakukan penyerangan ke Majapahit, hal ini lebih karena persaingan politik, bukan karena sentimen agama. Terlebih Majapahit lebih dahulu menyerang Giri Kedaton, sekutu Demak di Gresik. Di masa pemerintahannya, Demak memang masih menghadapi sejumlah konflik dengan sisa-sisa kekuatan Majapahit. Pada tahun 1479, Raden Patah meresmikan Masjid Agung Demak sebagai pusat pemerintahan. Ia juga memperkenalkan pemakaian Salokantara sebagai kitab undang-undang kerajaan.
Raden Patah mangkat pada tahun 1518 dan digantikan oleh menantunya, Adipati Unus atau Pangeran Sabrang Lor sebagai Sultan Demak II dengan gelar Alam Akbar at-Tsaniy (1518-1521). Raja kedua yang juga dikenal sebagai panglima pasukan gabungan Islam yang membawahi armada Demak, Banten dan Cirebon ini, kemudian gugur dalam pertempuran melawan Portugis di Malaka.
Pangeran Sabrang Lor digantikan oleh saudara iparnya yang kemudian bergelar Sultan Trenggana (1521-1548), tokoh yang banyak berjasa dalam penyebaran agama Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di masa pemerintahannya, Demak berhasil menghalau pasukan Portugis yang mendekati Sunda Kelapa sekaligus mengambil alih pelabuhan itu dari Kerajaan Pajajaran (1527). Hingga tahun 1546, wilayah Tuban, Madiun, Surabaya, Pasuruan, Malang hingga Blambangan - wilayah Hindu terakhir di ujung timur Jawa - pun berhasil dikuasainya.
Di masa kekuasaannya, muncul seorang pemuda bernama Jaka Tingkir, putra Ki Ageng Pengging - tokoh yang pernah dituduh memberontak dan dihukum mati -, yang justru datang mengabdi ke Demak. Kepiawaian Jaka Tingkir dalam olah keprajuritan berhasil memikat hati Sultan Trenggana yang kemudian mengangkatnya sebagai menantu sekaligus diangkat sebagai Bupati Pajang dengan nama Hadiwijaya.
Sultan Trenggana meninggal di tahun 1546 dan digantikan oleh Sunan Prawoto. Namun proses suksesi ini tidak berjalan mulus. Perang saudara dan perebutan kekuasaan yang menyertainya bahkan belakang berujung pada keruntuhan Kesultanan Demak. Bermula di tahun 1549 dengan terbunuhnya Sunan Prawoto oleh kaki tangan Arya Penangsang, Bupati Jipang, Ia adalah putra Pangeran Sekar Seda Lepen, saudara Sultan Trenggana yang terbunuh dalam perebutan kekuasaan pasca mangkatnya Pangeran Sabrang Lor di tahun 1521. Untuk merebut tahta kekuasaan di Demak, Kaki tangannya juga membunuh Pangeran Hadiri, menantu Sultan Trenggana yang menjabat Adipati Jepara. Mereka juga berupaya untuk membunuh Hadiwijaya, namun berhasil digagalkan.
Dengan dukungan para adipati di bawah kekuasaan Demak serta Ratu Kalinyamat, putri Sultan Trenggana sekaligus janda Pangeran Hadiri, Hadiwijaya beserta para pengikutnya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Tokoh ini akhirnya terbunuh di tangan Sutawijaya, anak angkat Hadiwijaya. Akhirnya, Hadiwijaya pun mewarisi kekuasaan Kesultanan Demak dan memindahkan ibukotanya ke Pajang. Belakangan, Pajang berdiri sebagai kesultanan sendiri di tahun 1568.
Pelabuhan Banten, semula dikenal dengan nama Banten Girang yang menjadi bagian dari kekuasaan Kerajaan Sunda Galuh yang beribukota di Pajajaran. Hubungan kerjasama ekonomi dan politik antara penguasa Sunda dan Portugis waktu itu, menimbulkan keresahan Kesultanan Demak, terlebih selepas kegagalan mereka mengenyahkan Portugis dari malaka di tahun 1513.
Karenanya, kedatangan armada Demak di Banten sekitar tahun 1526, selain membawa misi dakwah, juga demi mengamankan posisi kekuasaan dan keamanan Demak di sepanjang pesisir utara Jawa. Maulana Hasanuddin, putera Sunan Gunung Jati yang memimpin armada Demak, segera mendirikan pangkalan militer berbentuk benteng pertahanan yang diberi nama Surosowan yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan perdagangan. Di kemudian hari, Surosowan inilah yang akan menjelma menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Maulana Hasanuddin juga memperluas kekuasaan dan dakwahnya ke Lampung serta melakukan hubungan perdagangan dengan Sultan Munawar Syah dari kerajaan Inderapura di pesisir Sumatra Barat.
Setahun kemudian, Sultan Trenggana juga memerintah Maulana Hasanuddin bersama Fatahillah atau Falatehan untuk menaklukkan Pelabuhan Sunda Kelapa yang masih menjadi pelabuhan utama Kerajaan Sunda Galuh. Psaukan portugis berhasil diusir dan pelabuhan ini diberi nama baru: Jayakarta.
Setelah meninggalnya Sultan Trenggana di Demak, Banten yang semula berada di bawah kekuasaan Demak berangsur melepaskan diri. Keturunan Maulana Hasanuddin mulai membangun kerajaan sendiri. Maulana Yusuf, putra Maulana Hasanuddin, naik tahta pada tahun 1570 dan melanjutkan ekspansi ke pedalaman Sunda. Pajajaran, ibukota Kerajaan Sunda Galuh, berhasil ditaklukkan pada tahun 1579. Sebagai strategi untuk membatasi pergerakan Portugis, upaya penaklukkan Palembang dilakukan pada tahun 1596 oleh penggantinya, Maulana Muhammad. Sayang, upaya ini gagal, bahkan Maulana Muhammad meninggal dalam ekspedisi itu.
Di tahun 1638, putra Maulana Muhammad, Pangeran Ratu, tercatat sebagai raja pertama di Pulau Jawa yang menyematkan gelar ‘Sultan’ dan menggunakan nama Arab: Abu al-Mafakir Mahmud Abdulkadir. Pada masanya, Banten mulai aktif membina hubungan diplomatik dengan para penguasa Eropa, diantaranya melalui korespondensi yang dilakukannya dengan Raja James I di Inggris (1605) dan Charles I (1629).
Pada pertengahan abad ke-17, Kesultanan Banten telah berkembang sebagai kerajaan maritim sekaligus pusat perdagangan penting di kawasan Nusantara. Aktifitas perdagangannya yang begitu dinamis juga membuat Banten sebagai sebuah kawasan multi etnis yang menjalin hubungan perdagangan dengan orang-orang Inggris, Denmark, Tionghoa, Persia, India, Siam, Vietnam, Philipina, serta Jepang.
Kesultanan Banten mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1682). Pada masanya, Banten memiliki armada laut yang sangat mengesankan yang dibangun menyerupai armada-armada Eropa. Sultan juga mengupah orang-orang Eropa untuk bekerja di Kesultanan Banten, sesuai dengan beragam keahlian yang dimilikinya. Saat itu, Banten juga mampu mengimbangi kekuatan VOC di Batavia yang sebelumnya pernah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang yang berlayar menuju Banten.
Sayang, diujung masa pemerintahannya, Sultan Ageng Tirtayasa berselisih paham dengan Sultan Haji, putranya sendiri. keterlibatan VOC dalam konflik keluarga itu berakibat pada pecahnya perang saudara di Kesultanan Banten, yang berakhir dengan kemenangan pihak Sultan Haji yang didukung penuh oleh VOC.
Sebagaimana lazimnya, dukungan ini harus dibayar mahal dengan berbagai konsesi dan kompensasi. Ketika Sultan Haji meninggal tahun 1687, cengkeram pengaruh VOC di Banten semakin kuat. Setiap pengangkatan para Sultan Banten harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal di Batavia. Meski berbagai perlawanan terhadap hegemoni VOC telah dilakukan, takdir sejarah kemudian menempatkan Kesultanan Banten menjadi vassal dari VOC di Batavia sejak tahun 1752.
Puncak keruntuhan Banten terjadi di tahun 1808 saat Istana Surosowan di kota Intan yang menjadi simbol kekuasaan Kesultanan Banten dihancurkan oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels menjelang pembangunan Jalan Raya Pos. Lima tahun kemudian, di tahun 1813, Kesultanan Banten resmi dihapus oleh Pemerintah kolonial Inggris, setelah Thomas Stamford Raffles melucuti dan dan menurunkan tahta Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainussalihin, sultan terakhir Banten.
Kisah tentang Cirebon diawali saat Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi di Pajajaran, mendirikan Kraton Pakungwati dan membentuk pemerintahan pertama di Cirebon. Keturunan Kerajaan Sunda yang telah memeluk agama Islam dan aktif berdakwah ini kemudian dianggap sebagai raja pertama di Cirebon sebelum terbentuknya kesultanan. Pada tahun 1479, kedudukannya sebagai penguasa Cirebon digantikan oleh Syarif Hidayatullah, keponakannya yang menjabat sebagai panglima perang Demak.
Tahun 1552, Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Cirebon dan bertahta dengan gelar Tumenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah atau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Pada masanya, Cirebon berkembang sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati sendiri kemudian diyakini sebagai pendiri dinasti Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten.
Sepeninggal Syarif Hidayatullah di tahun 1568, kedudukannya digantikan oleh Fatahillah atau Falatehan, mantan panglima perang Kesultanan Pasai yang di tahun 1527 pernah mengusir Portugis dari pelabuhan Sunda Kelapa. Pemerintahan Fatahillah hanya berlangsung selama dua tahun karena kemudian meninggal di tahun 1570. Karena tidak ada calon lain yang dianggap layak, tahta Kesultanan Cirebon kemudian jatuh ke tangan Pangeran Mas, cucu Sunan Gunung Jati, yang kemudian bergelar Panembahan Ratu I (1570-1649).
Ketika Panembahan Ratu I meninggal tahun 1649, tahta Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh cucunya, Pangeran Rasmi, karena putra mahkota Pangeran Seda ing Gayam, ayah Pangeran Rasmi, meninggal lebih dahulu. Pangeran Rasmi kemudian menggunakan nama gelar ayahnya, yaitu Panembahan Adiningkusumah atau dikenal pula sebagai Panembahan Ratu II.
Dalam masa pemerintahannya, Panembahan Ratu II yang kebetulan adalah menantu dari Amangkurat I di Kesultanan Mataram, terhimpit di antara dua kekuatan besar yang saling berebut pengaruh, Kesultanan Banten dibawah Sultan Ageng Tirtayasa dan Kesultanan Mataram yang dikuasai oleh mertuanya. Cirebon selalu berada dalam posisi dicurigai oleh kedua pihak atas kedekatannya dengan pihak lain. Kondisi ini berubah menjadi krisis politik ketika Panembahan Ratu II meninggal dunia di Kartasura (1662) dan dua orang putranya, Pangeran Mertawijaya dan Pangeran Kertawijaya tertahan di Mataram. Panembahan Ratu II kemudian dimakamkan di bukit Girilaya, sehingga kemudian juga dikenal dengan nama Panembahan Girilaya.
Inilah awal rangkaian perpecahan di Kesultanan Cirebon. Perpecahan pertama terjadi saat penentuan siapa dari tiga putra Panembahan Girilaya yang akan mengisi kekosongan tahta Kesultanan Cirebon: Pangeran Mertawijaya, Pangeran Kertawijaya, ataukah Pangeran Wangsakerta. Keputusannya ada di tangan Sultan Ageng Tirtayasa, sebagai balas budi atas bantuannya kepada Pangeran Wangsakerta terkait nasib Pangeran Mertawijaya dan Pangeran Kertawijaya selama di Mataram. Sultan Banten ini, yang dengan bantuan pemberontak Trunojoyo berhasil menyelamatkan nasib kedua saudara Pangeran Wangsakerta, mengambil kesempatan untuk melakukan taktik devide et impera agar Cirebon melemah dan tak lagi terlalu dekat dengan Mataram.
Sultan Banten kemudian mengangkat kedua pangeran yang diselamatkannya sebagai Sultan Cirebon. Pangeran Mertawijaya ditetapkan sebagai Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsudin (1677-1703) dan Pangeran Kertawijaya diangkat sebagai Sultan Keraton Kanoman Cirebon dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badrudin (1677-1723). Sementara Pangeran Wangsakerta ‘hanya’ diangkat sebagai Panembahan Cirebon dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasarudin atau Panembahan Tohpati (1677-1713).
Sebagai sultan, Pangeran Mertawijaya dan Pangeran Kertawijaya mempunyai wilayah dan kedaulatan penuh berikut rakyat dan keratonnya masing-masing. Sementara Pangeran Wangsakerta tidak memiliki wilayah kekuasaan atau keraton sendiri, namun berdiri sebagai kaprabonan atau paguron, yaitu tempat menimba ilmu di kalangan intelektual Keraton Cirebon.
Perpecahan kedua terjadi pada masa pemerintahan Sultan Anom IV (1798-1803), ketika salah satu putranya, Pangeran Raja Kanoman berkehendak membangun kesultanan sendiri dengan nama Kacirebonan. Niat disintegrasi ini dengan mudah diamini oleh Pemerintah Hindia Belanda. Albertus H. Wiese, Gubernur Jenderal yang berkuasa pada tahun 1807 segera mengeluarkan besluit yang menetapkannya sebagai Sultan Carbon Kacirebonan, dengan syarat bahwa putra dan para penggantinya tidak berhak atas gelar sultan, cukup dengan gelar pangeran.
Sejak saat itulah Kesultanan Cirebon terbagi menjadi empat kekuasaan: Kasepuhan, Kanoman, Kaprabonan dan Kacirebonan. Ketika Pemerintah Hindia Belanda memutuskan pengesahan pembentukan Gemeente Cheirebon atau Kota Cirebon di tahun 1906 dan 1926, kekuasaan pemerintahan Kesultanan Cirebon pun secara resmi dihapuskan.
Peta ini segera berubah ketika kekuasaan Majapahit mulai surut dan disusul dengan munculnya pusat-pusat kekuasaan Islam, khususnya di Demak, Banten dan Cirebon. Pada saat yang sama, persaingan dakwah dan perniagaan di kawasan Asia Tenggara meningkat pesat, terlebih dengan jatuhnya Malaka (1511) dan Samudera pasai (1512) ke tangan Portugis. Demak, Banten dan Cirebon pun sempat beraliansi merapatkan barisan untuk mencegah pengaruh dominasi Portugis di tanah Jawa.
Bermula dari sebuah kadipaten di wilayah pesisir, Demak muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi kebesaran Majapahit yang semakin surut. Kota pelabuhan ini dibangun pada tahun 1475 oleh Raden Patah yang kemudian bertahta sebagai Sultan Demak I dengan gelar Alam Akbar al Fattah (1500-1518).
Raden Patah dikenal sebagai pemimpin yang sangat toleran. Kuil Sam Po Kong di Semarang yang dibangun oleh Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam, tidak dipaksa untuk mengembalikan fungsinya sebagai masjid. Atas wasiat Sunan Ampel, Raden Patah juga tidak mau memerangi umat Hindu dan Buddha. Meski sempat melakukan penyerangan ke Majapahit, hal ini lebih karena persaingan politik, bukan karena sentimen agama. Terlebih Majapahit lebih dahulu menyerang Giri Kedaton, sekutu Demak di Gresik. Di masa pemerintahannya, Demak memang masih menghadapi sejumlah konflik dengan sisa-sisa kekuatan Majapahit. Pada tahun 1479, Raden Patah meresmikan Masjid Agung Demak sebagai pusat pemerintahan. Ia juga memperkenalkan pemakaian Salokantara sebagai kitab undang-undang kerajaan.
Raden Patah mangkat pada tahun 1518 dan digantikan oleh menantunya, Adipati Unus atau Pangeran Sabrang Lor sebagai Sultan Demak II dengan gelar Alam Akbar at-Tsaniy (1518-1521). Raja kedua yang juga dikenal sebagai panglima pasukan gabungan Islam yang membawahi armada Demak, Banten dan Cirebon ini, kemudian gugur dalam pertempuran melawan Portugis di Malaka.
Pangeran Sabrang Lor digantikan oleh saudara iparnya yang kemudian bergelar Sultan Trenggana (1521-1548), tokoh yang banyak berjasa dalam penyebaran agama Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di masa pemerintahannya, Demak berhasil menghalau pasukan Portugis yang mendekati Sunda Kelapa sekaligus mengambil alih pelabuhan itu dari Kerajaan Pajajaran (1527). Hingga tahun 1546, wilayah Tuban, Madiun, Surabaya, Pasuruan, Malang hingga Blambangan - wilayah Hindu terakhir di ujung timur Jawa - pun berhasil dikuasainya.
Di masa kekuasaannya, muncul seorang pemuda bernama Jaka Tingkir, putra Ki Ageng Pengging - tokoh yang pernah dituduh memberontak dan dihukum mati -, yang justru datang mengabdi ke Demak. Kepiawaian Jaka Tingkir dalam olah keprajuritan berhasil memikat hati Sultan Trenggana yang kemudian mengangkatnya sebagai menantu sekaligus diangkat sebagai Bupati Pajang dengan nama Hadiwijaya.
Sultan Trenggana meninggal di tahun 1546 dan digantikan oleh Sunan Prawoto. Namun proses suksesi ini tidak berjalan mulus. Perang saudara dan perebutan kekuasaan yang menyertainya bahkan belakang berujung pada keruntuhan Kesultanan Demak. Bermula di tahun 1549 dengan terbunuhnya Sunan Prawoto oleh kaki tangan Arya Penangsang, Bupati Jipang, Ia adalah putra Pangeran Sekar Seda Lepen, saudara Sultan Trenggana yang terbunuh dalam perebutan kekuasaan pasca mangkatnya Pangeran Sabrang Lor di tahun 1521. Untuk merebut tahta kekuasaan di Demak, Kaki tangannya juga membunuh Pangeran Hadiri, menantu Sultan Trenggana yang menjabat Adipati Jepara. Mereka juga berupaya untuk membunuh Hadiwijaya, namun berhasil digagalkan.
Dengan dukungan para adipati di bawah kekuasaan Demak serta Ratu Kalinyamat, putri Sultan Trenggana sekaligus janda Pangeran Hadiri, Hadiwijaya beserta para pengikutnya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Tokoh ini akhirnya terbunuh di tangan Sutawijaya, anak angkat Hadiwijaya. Akhirnya, Hadiwijaya pun mewarisi kekuasaan Kesultanan Demak dan memindahkan ibukotanya ke Pajang. Belakangan, Pajang berdiri sebagai kesultanan sendiri di tahun 1568.
Pelabuhan Banten, semula dikenal dengan nama Banten Girang yang menjadi bagian dari kekuasaan Kerajaan Sunda Galuh yang beribukota di Pajajaran. Hubungan kerjasama ekonomi dan politik antara penguasa Sunda dan Portugis waktu itu, menimbulkan keresahan Kesultanan Demak, terlebih selepas kegagalan mereka mengenyahkan Portugis dari malaka di tahun 1513.
Karenanya, kedatangan armada Demak di Banten sekitar tahun 1526, selain membawa misi dakwah, juga demi mengamankan posisi kekuasaan dan keamanan Demak di sepanjang pesisir utara Jawa. Maulana Hasanuddin, putera Sunan Gunung Jati yang memimpin armada Demak, segera mendirikan pangkalan militer berbentuk benteng pertahanan yang diberi nama Surosowan yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan perdagangan. Di kemudian hari, Surosowan inilah yang akan menjelma menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Maulana Hasanuddin juga memperluas kekuasaan dan dakwahnya ke Lampung serta melakukan hubungan perdagangan dengan Sultan Munawar Syah dari kerajaan Inderapura di pesisir Sumatra Barat.
Setahun kemudian, Sultan Trenggana juga memerintah Maulana Hasanuddin bersama Fatahillah atau Falatehan untuk menaklukkan Pelabuhan Sunda Kelapa yang masih menjadi pelabuhan utama Kerajaan Sunda Galuh. Psaukan portugis berhasil diusir dan pelabuhan ini diberi nama baru: Jayakarta.
Setelah meninggalnya Sultan Trenggana di Demak, Banten yang semula berada di bawah kekuasaan Demak berangsur melepaskan diri. Keturunan Maulana Hasanuddin mulai membangun kerajaan sendiri. Maulana Yusuf, putra Maulana Hasanuddin, naik tahta pada tahun 1570 dan melanjutkan ekspansi ke pedalaman Sunda. Pajajaran, ibukota Kerajaan Sunda Galuh, berhasil ditaklukkan pada tahun 1579. Sebagai strategi untuk membatasi pergerakan Portugis, upaya penaklukkan Palembang dilakukan pada tahun 1596 oleh penggantinya, Maulana Muhammad. Sayang, upaya ini gagal, bahkan Maulana Muhammad meninggal dalam ekspedisi itu.
Di tahun 1638, putra Maulana Muhammad, Pangeran Ratu, tercatat sebagai raja pertama di Pulau Jawa yang menyematkan gelar ‘Sultan’ dan menggunakan nama Arab: Abu al-Mafakir Mahmud Abdulkadir. Pada masanya, Banten mulai aktif membina hubungan diplomatik dengan para penguasa Eropa, diantaranya melalui korespondensi yang dilakukannya dengan Raja James I di Inggris (1605) dan Charles I (1629).
Pada pertengahan abad ke-17, Kesultanan Banten telah berkembang sebagai kerajaan maritim sekaligus pusat perdagangan penting di kawasan Nusantara. Aktifitas perdagangannya yang begitu dinamis juga membuat Banten sebagai sebuah kawasan multi etnis yang menjalin hubungan perdagangan dengan orang-orang Inggris, Denmark, Tionghoa, Persia, India, Siam, Vietnam, Philipina, serta Jepang.
Kesultanan Banten mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1682). Pada masanya, Banten memiliki armada laut yang sangat mengesankan yang dibangun menyerupai armada-armada Eropa. Sultan juga mengupah orang-orang Eropa untuk bekerja di Kesultanan Banten, sesuai dengan beragam keahlian yang dimilikinya. Saat itu, Banten juga mampu mengimbangi kekuatan VOC di Batavia yang sebelumnya pernah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang yang berlayar menuju Banten.
Sayang, diujung masa pemerintahannya, Sultan Ageng Tirtayasa berselisih paham dengan Sultan Haji, putranya sendiri. keterlibatan VOC dalam konflik keluarga itu berakibat pada pecahnya perang saudara di Kesultanan Banten, yang berakhir dengan kemenangan pihak Sultan Haji yang didukung penuh oleh VOC.
Sebagaimana lazimnya, dukungan ini harus dibayar mahal dengan berbagai konsesi dan kompensasi. Ketika Sultan Haji meninggal tahun 1687, cengkeram pengaruh VOC di Banten semakin kuat. Setiap pengangkatan para Sultan Banten harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal di Batavia. Meski berbagai perlawanan terhadap hegemoni VOC telah dilakukan, takdir sejarah kemudian menempatkan Kesultanan Banten menjadi vassal dari VOC di Batavia sejak tahun 1752.
Puncak keruntuhan Banten terjadi di tahun 1808 saat Istana Surosowan di kota Intan yang menjadi simbol kekuasaan Kesultanan Banten dihancurkan oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels menjelang pembangunan Jalan Raya Pos. Lima tahun kemudian, di tahun 1813, Kesultanan Banten resmi dihapus oleh Pemerintah kolonial Inggris, setelah Thomas Stamford Raffles melucuti dan dan menurunkan tahta Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainussalihin, sultan terakhir Banten.
Kisah tentang Cirebon diawali saat Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi di Pajajaran, mendirikan Kraton Pakungwati dan membentuk pemerintahan pertama di Cirebon. Keturunan Kerajaan Sunda yang telah memeluk agama Islam dan aktif berdakwah ini kemudian dianggap sebagai raja pertama di Cirebon sebelum terbentuknya kesultanan. Pada tahun 1479, kedudukannya sebagai penguasa Cirebon digantikan oleh Syarif Hidayatullah, keponakannya yang menjabat sebagai panglima perang Demak.
Tahun 1552, Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Cirebon dan bertahta dengan gelar Tumenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah atau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Pada masanya, Cirebon berkembang sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati sendiri kemudian diyakini sebagai pendiri dinasti Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten.
Sepeninggal Syarif Hidayatullah di tahun 1568, kedudukannya digantikan oleh Fatahillah atau Falatehan, mantan panglima perang Kesultanan Pasai yang di tahun 1527 pernah mengusir Portugis dari pelabuhan Sunda Kelapa. Pemerintahan Fatahillah hanya berlangsung selama dua tahun karena kemudian meninggal di tahun 1570. Karena tidak ada calon lain yang dianggap layak, tahta Kesultanan Cirebon kemudian jatuh ke tangan Pangeran Mas, cucu Sunan Gunung Jati, yang kemudian bergelar Panembahan Ratu I (1570-1649).
Ketika Panembahan Ratu I meninggal tahun 1649, tahta Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh cucunya, Pangeran Rasmi, karena putra mahkota Pangeran Seda ing Gayam, ayah Pangeran Rasmi, meninggal lebih dahulu. Pangeran Rasmi kemudian menggunakan nama gelar ayahnya, yaitu Panembahan Adiningkusumah atau dikenal pula sebagai Panembahan Ratu II.
Dalam masa pemerintahannya, Panembahan Ratu II yang kebetulan adalah menantu dari Amangkurat I di Kesultanan Mataram, terhimpit di antara dua kekuatan besar yang saling berebut pengaruh, Kesultanan Banten dibawah Sultan Ageng Tirtayasa dan Kesultanan Mataram yang dikuasai oleh mertuanya. Cirebon selalu berada dalam posisi dicurigai oleh kedua pihak atas kedekatannya dengan pihak lain. Kondisi ini berubah menjadi krisis politik ketika Panembahan Ratu II meninggal dunia di Kartasura (1662) dan dua orang putranya, Pangeran Mertawijaya dan Pangeran Kertawijaya tertahan di Mataram. Panembahan Ratu II kemudian dimakamkan di bukit Girilaya, sehingga kemudian juga dikenal dengan nama Panembahan Girilaya.
Inilah awal rangkaian perpecahan di Kesultanan Cirebon. Perpecahan pertama terjadi saat penentuan siapa dari tiga putra Panembahan Girilaya yang akan mengisi kekosongan tahta Kesultanan Cirebon: Pangeran Mertawijaya, Pangeran Kertawijaya, ataukah Pangeran Wangsakerta. Keputusannya ada di tangan Sultan Ageng Tirtayasa, sebagai balas budi atas bantuannya kepada Pangeran Wangsakerta terkait nasib Pangeran Mertawijaya dan Pangeran Kertawijaya selama di Mataram. Sultan Banten ini, yang dengan bantuan pemberontak Trunojoyo berhasil menyelamatkan nasib kedua saudara Pangeran Wangsakerta, mengambil kesempatan untuk melakukan taktik devide et impera agar Cirebon melemah dan tak lagi terlalu dekat dengan Mataram.
Sultan Banten kemudian mengangkat kedua pangeran yang diselamatkannya sebagai Sultan Cirebon. Pangeran Mertawijaya ditetapkan sebagai Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsudin (1677-1703) dan Pangeran Kertawijaya diangkat sebagai Sultan Keraton Kanoman Cirebon dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badrudin (1677-1723). Sementara Pangeran Wangsakerta ‘hanya’ diangkat sebagai Panembahan Cirebon dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasarudin atau Panembahan Tohpati (1677-1713).
Sebagai sultan, Pangeran Mertawijaya dan Pangeran Kertawijaya mempunyai wilayah dan kedaulatan penuh berikut rakyat dan keratonnya masing-masing. Sementara Pangeran Wangsakerta tidak memiliki wilayah kekuasaan atau keraton sendiri, namun berdiri sebagai kaprabonan atau paguron, yaitu tempat menimba ilmu di kalangan intelektual Keraton Cirebon.
Perpecahan kedua terjadi pada masa pemerintahan Sultan Anom IV (1798-1803), ketika salah satu putranya, Pangeran Raja Kanoman berkehendak membangun kesultanan sendiri dengan nama Kacirebonan. Niat disintegrasi ini dengan mudah diamini oleh Pemerintah Hindia Belanda. Albertus H. Wiese, Gubernur Jenderal yang berkuasa pada tahun 1807 segera mengeluarkan besluit yang menetapkannya sebagai Sultan Carbon Kacirebonan, dengan syarat bahwa putra dan para penggantinya tidak berhak atas gelar sultan, cukup dengan gelar pangeran.
Sejak saat itulah Kesultanan Cirebon terbagi menjadi empat kekuasaan: Kasepuhan, Kanoman, Kaprabonan dan Kacirebonan. Ketika Pemerintah Hindia Belanda memutuskan pengesahan pembentukan Gemeente Cheirebon atau Kota Cirebon di tahun 1906 dan 1926, kekuasaan pemerintahan Kesultanan Cirebon pun secara resmi dihapuskan.
Teks: Agus Yuniarso; Foto: Albert
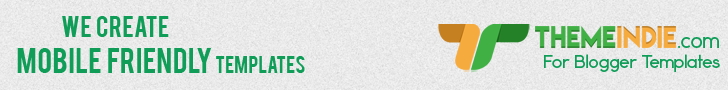




This post have 0 komentar
EmoticonEmoticon